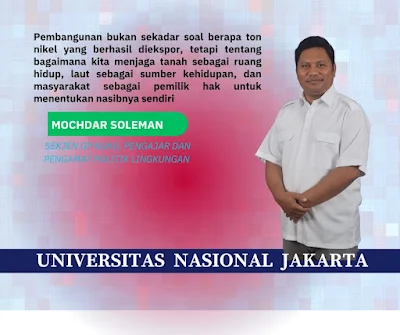Pembangunan atau Perampasan? Peran Sherly Tjoanda di Tengah Krisis Ekologis Maluku Utara
Maluku Utara: Antara Pertumbuhan dan Ketimpangan
Maluku Utara mengalami lonjakan pembangunan signifikan dalam dua dekade terakhir. Dari provinsi agraris-pesisir, kini wilayah ini berubah menjadi episentrum industri nikel nasional.
Pemerintah pusat mendorong provinsi ini sebagai lokomotif ekonomi hijau, dengan deretan smelter, pelabuhan, dan investasi asing yang masif.
Namun, kemajuan itu menyimpan paradoks. Di balik pertumbuhan ekonomi dua digit dan infrastruktur modern, tersimpan jejak
deforestasi, marginalisasi masyarakat adat, serta ketimpangan sosial yang makin melebar. Contoh konkret terlihat di Gebe, Maba, dan Weda—tiga wilayah yang kini menjadi “zona merah” ketegangan antara rakyat dan industri tambang.
Sherly Tjoanda: Figur Sentral dalam Konstelasi Politik-Ekonomi Maluku Utara
Di tengah dinamika tersebut, nama Sherly Tjoanda, politisi perempuan asal Maluku Utara, mencuat sebagai aktor penting. Ia kini menjabat sebagai Gubernur dan dianggap memiliki pengaruh besar dalam perizinan tambang dan perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.
Pertanyaannya: Apakah Sherly Tjoanda memperjuangkan kepentingan rakyat atau justru mengonsolidasikan kuasa modal?
Kapitalisme Ekstraktif dan Alienasi Ekologis
Karl Marx menggambarkan kapitalisme sebagai proses perampasan sarana produksi dari tangan rakyat. Di Maluku Utara, hal ini terjadi secara sistematis. Lebih dari 95.000 hektare lahan di Halmahera Tengah telah dikuasai izin tambang, termasuk PT IWIP yang memiliki konsesi seluas 45.045 hektare.
Laporan JATAM, WALHI, dan Trend Asia (2023) menunjukkan dampak serius: deforestasi, pencemaran air tanah, sedimentasi laut, dan perpindahan paksa masyarakat desa. Di Pulau Gebe dan Maba, hutan adat berubah menjadi kawasan tambang, sementara nelayan di Weda dan Pakal kehilangan ruang tangkap mereka.
Simon Clarke menegaskan, infrastruktur seperti smelter dan pelabuhan bukan hanya simbol kemajuan, tetapi instrumen dominasi ruang. Ketika masyarakat adat kehilangan tanah dan akses laut, maka terjadi alienasi ekologis—keterasingan manusia dari lingkungan hidupnya.
Patronase Politik dan Negara Bayangan
Teori Liddle dan Schulte Nordholt
mengungkap bahwa negara di negara berkembang sering tidak netral, melainkan arena patronase. Di Maluku Utara, Sherly Tjoanda memainkan peran ganda: sebagai pejabat publik dan sebagai penghubung antara modal dan kebijakan.
Peran ini terlihat dari keterlibatannya dalam proyek-proyek industri strategis, perizinan tambang, hingga respon terhadap konflik sosial. Pemerintah daerah kerap dianggap lebih melindungi investasi daripada rakyat. Ketika warga menolak tambang atau mempertanyakan AMDAL, mereka justru dikriminalisasi atau dihadapkan pada aparat keamanan.
Hal ini mencerminkan praktik “negara bayangan”, di mana kekuasaan informal elite lokal mengalahkan aturan formal negara.
Kebutuhan Mendesak: Redefinisi Arah Pembangunan
Pembangunan yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan distribusi hanya akan melanggengkan kolonialisme sumber daya. Sudah saatnya Maluku Utara mengadopsi paradigma demokrasi ekologis:
Menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan
Mengakui hak atas tanah, laut, dan udara
Membangun sistem politik yang tidak tunduk pada patronase modal
Peran Sherly Tjoanda sangat menentukan. Jika ia menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang pola investasi ekstraktif dan membela hak masyarakat terdampak, maka ia bisa menjadi pemimpin transformatif.
Namun jika ia terus memperkuat relasi kuasa yang timpang, maka sejarah akan mencatatnya sebagai bagian dari kegagalan pembangunan yang berkeadilan.
Penutup: Pembangunan untuk Siapa?